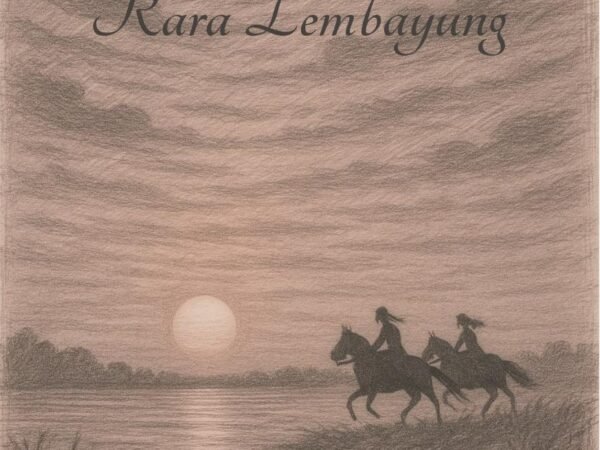- MAN 1 GUNUNGKIDUL MANTAP - MANDIRI - AKHLAKUL KARIMAH - NASIONALIS - TERAMPIL - ADAPTIF - PRESTASI
- MAN 1 GUNUNGKIDUL MANTAP - MANDIRI - AKHLAKUL KARIMAH - NASIONALIS - TERAMPIL - ADAPTIF - PRESTASI
Langit di Balik Jeruji

Oleh : Tuti Herawati, S.Pd.,
Guru Bimbingan Konseling MAN 1 Gunungkidul
-=-=-=-
Langit, gadis berusia lima belas tahun, duduk memeluk lutut di sudut kamarnya. Dari luar, terdengar suara piring pecah diiringi teriakan yang memekakkan telinga. Sejak kecil, rumahnya bukanlah tempat aman. Bentakan adalah bahasa sehari-hari, dan tamparan menjadi tanda bahwa ia “salah” menurut aturan keluarganya. Mereka menyebutnya adat, tapi bagi Langit, itu hanyalah jeruji yang tak terlihat. Jeruji yang mengurung dirinya, meski tak terbuat dari besi.

Di sekolah, Langit menjadi murid yang pendiam. Senyumnya tipis, tak pernah menembus matanya. Ia belajar mengemas luka dalam diam, menyembunyikannya di balik lengan baju panjang. Namun suatu hari, di ruang konseling, Bu Ratri menatapnya lebih lama dari biasanya. “Kamu terlihat lelah sekali,” ucap Bu Ratri pelan. Pertanyaan itu seperti kunci yang membuka pintu rapuh dalam dirinya. Air mata Langit pun mengalir tanpa diminta, menceritakan kisah yang selama ini ia pendam.
Malamnya, Langit menulis di buku harian: “Apakah bertahan berarti hidup, atau justru mati perlahan?” Ia mencintai keluarganya, tapi merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia ingin menulis lagu, bermusik, dan memilih jalan hidupnya sendiri. Namun semua itu dianggap pembangkangan. Pilihannya hanya dua: tetap tinggal di balik jeruji atau melompat tanpa tahu ke mana.
Hari-hari berikutnya, Bu Ratri mengajaknya berbicara lebih sering. Ia menggunakan berbagai teknik konseling: mendengar tanpa menghakimi, memberi ruang diam ketika Langit sulit bicara, memintanya menggambar perasaannya, bahkan menulis surat untuk dirinya di masa depan. Sedikit demi sedikit, Langit mulai menemukan kata-kata untuk lukanya, dan keberanian untuk memimpikan masa depan tanpa rasa takut. Pelan-pelan, Langit mulai melihat secercah kebebasan: ikut ekstrakurikuler musik, membaca puisi di panggung sekolah, dan menulis lirik-lirik yang tak lagi hanya berisi kesedihan. Jeruji itu masih ada, tapi kini ia tahu bahwa jeruji bisa dilewati, sedikit demi sedikit, tanpa kehilangan diri.
Suatu pagi, ia berdiri di depan cermin dengan rambut tergerai dan mata yang lebih hidup. “Aku bukan bayangan kalian,” bisiknya, “aku adalah aku”. Langit belum sepenuhnya bebas, tapi ia sudah menemukan kunci pertama: keberanian. Dan itu, ia tahu, akan membawanya terbang melewati langit yang selama ini ia pandang dari balik jeruji.